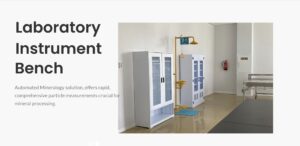Mahatma Gandhi berpendapat bahwa salah satu kesalahan fatal peradaban ialah proses pendidikan tanpa karakter (Education without Character). Dr. Martin Luther King juga melontarkan tesis senada, “Intelligence plus character, that is the goal of true education.” Kecerdasan plus karakter, itulah sebenarnya tujuan akhir pendidikan manusia. Seruan kedua tokoh di muta menemukan relevansinya kini. Tatkala para koruptor menjarah Republik tercinta. Walau bergelar akademik strata 1 – Ph.D tega merampok uang rakyat secara sistemik. Di mana nurani kemanusiaan mereka? Padahal penggali pasir di Dusun Karang Klethak, hanya berupah Rp 60.000/truk. Setiap truk pasir dikerjakan 2-3 orang. Pun hasilnya harus dibagi rata. Para penambang tradisional di tepi Kali Boyong itu mengais sisa lahar dingin Merapi.
Belajar dari realitas sosial tersebut, Yayasan Dwi Bhakti – lembaga pendidikan yang mengelola beberapa sekolah di Bandar Lampung, Jakarta, dan Klaten – menyediakan waktu hening untuk bersyukur dan mengasah kepekaan. Terutama sebelum memulai aktivitas pembelajaran. Renungan harian yang termaktub dalam buku ini menjadi titik pijak reflektif mereka. “Lighting Candles” berisi 150 kisah inspiratif. Bila Anda memasuki kompleks keluarga besar SMP Fransiskus Tanjung Karang (Fransita) pada jam 07.00-07.15 WIB cerita-cerita inilah yang menggema. Sembari diiringi alunan pujian bagi-Nya. Kumpulan renungan remaja ini diterbitkan untuk merayakan rangkaian Yubelium SD-SMP Fransita pada 2010-2011.
Simaklah kisah berikut. Konon seseorang kehilangan jam tangan di tumpukan jerami. Sepanjang hari bersama temannya ia sibuk mencari, namun sia-sia saja. Akhirnya, mereka menyerah dan pulang. Lantas, datanglah adiknya, sendirian ia tidur menempelkan telinga di atas tumpukan jerami. Suasana sedemikian hening, sehingga ia dapat mendengar detak jarum jam. Si adik berhasil menemukan jam tangan tersebut.
Saat kakaknya bertanya, bagaimana ia dapat menemukan jamnya, ia menjawab lugu, “Saya hanya tidur dan menempelkan telinga di atas tumpukan jerami itu dan berusaha sehening mungkin, lalu saya dapat mendengar detak jarum jam.” (Hlm 109). Manusia seringkali begitu sibuk. Kehidupan modern mensyaratkan kompetisi. Dalam konteks ini, tak ada ruginya mengheningkan cipta dan rehat sejenak. Sehingga suara nurani terdengar jelas kembali.
Tumbuh
Alkisah 2 biji tanaman tergeletak berdampingan. Biji pertama berkata, “Aku ingin tumbuh! Aku ingin menancapkan akarku dalam-dalam ke tanah. Aku akan menusukkan kecambahku untuk menembus lapisan tanah di atasku. Aku ingin menebarkan kuncupku yang lembut laksana panji-panji nan mendaraskan kedatangan musim semi. Aku hendak menikmati kehangatan mentari di wajahku, serta tetes embun pagi di atas kuntum bungaku. Dan ia pun tumbuh.
Sebaliknya, biji kedua berujar, “Aku takut. Kalau aku mengarahkan akarku ke tanah ke bawah sana. Aku tidak tahu apa yang akan kuhadapi dalam kegelapan. Bila aku mencari jalan lewat tanah yang keras di atas sana, boleh jadi aku akan merusak kecambahku yang halus. Bagaimana pula kalau aku membiarkan pucukku terbuka dan seekor bekicot melalapnya? Dan bila aku memekarkan kembangku, seorang anak kecil mungkin akan merenggutku dari tanah. Tidak! Jauh lebih baik bagiku menanti di sini sampai keadaan menjadi aman. Dan ia pun menunggu.
Lantas, seekor ayam mengais-ais mencari makan. Akhirnya ia menemukan biji yang tengah menunggu itu. Secepat kilat si ayam menyambarnya. Manusia membutuhkan keberanian untuk bertumbuh. Keberanian bukan untuk mengalahkan orang lain, melainkan mengalahkan diri sendiri. Seringkali kesulitan terbesar mencapai keberhasilan justru datang dari dalam diri. Keberanaian bersikap tegas terhadap diri sendiri memang tidak enak. Namun inilah cara meraih keberhasilan dalam hidup. Mari belajar dari biji pertama yang mengalahkan ketakutannya sendiri. Begitulah pesan moral dari kisah, “Menerjang Resiko,” (halaman 141).
Persahabatan
Perihal persahabatan, ada sebuah cerita apik dalam buku ini. 2 sahabat miskin ingin bersekolah. Tapi kedua orang tersebut berasal dari keluarga miskin. Lantas, pergilah mereka ke kota. Mengingat ongkos pendidikan tinggi, berundinglah keduanya. Orang pertama berkata, “Biarlah kamu saja yang sekolah, aku yang bekerja, nanti setelah lulus baru aku yang sekolah.” Orang kedua menjawab, “Tidak kamu sajalah yang sekolah, aku yang bekerja!” Keduanya ngotot, tapi akhirnya salah satu mengalah dan mau bersekolah.
Toni belajar dengan giat, sampai lulus dan berpredikat sangat memuaskan. Sedangkan temannya bekerja siang-malam sebagai buruh pabrik. Apapun dilakukan asal mendapat uang untuk biaya studi. Pada suatu ketika, pulanglah Toni ke rumah temannya. Sebelum mengetuk pintu, ia mendengar kawannya (sedang sekarat) berdoa, “Ya Tuhan, biarlah sahabatku Toni belajar dan lindungi dia selalu, berilah kekuatan agar cita-cita kami tercapai. Jari-jariku mati, tulang-tulangku tak mampu bergerak lagi…” Sahabatnya itu akhirnya meninggal.
Guna mengenang kebaikan sahabtanya, Toni menggambar sebuah lukisan “Tangan Yang Berdoa.” Pun sampai sekarang dipasang orang di banyak rumah, sebagai hiasan dinding. Lukisan itu menyiratkan persahabatan mendalam. Ia memampukan seseorang mengorbankan nyawa bagi sahabat tercinta (halaman 212). Apakah para pemimpin kita memiliki rasa persahabatan semacam itu dengan para konstituennya?
Buku ini juga mengungkap formula sukses. Yakni piawai bekerjasama dengan sesama dan sudi berbagi. Ironisnya, banyak orang menjalani kehidupan dengan “sengat” siap menyerang. Padahal lebah pun siap saling memberi makan. Bahkan walau berasal dari koloni berbeda. Mereka sudi bekerjasama dan saling memberi. Lebah tak pernah menyerang sesama spesies. Ia hanya memakai “sengat” untuk pertahanan diri. Para lebah berusaha bersama mempersembahkan yang terbaik tanpa mempermasalahkan posisi dan jabatan dalam koloni.
Sebaliknya, manusia justru sering mengeluarkan kata-kata menyengat pada sesama. Bukan sebagai pertahanan diri melainkan sebagai pelampiasan dendam. Kita perlu belajar dari lebah dalam menjalani hidup bersama dengan tetangga sebelah. Belajar diam jika kata-kata yang terucap justru ungkapan keegoisan. Saatnya belajar berkata dengan bijak dan tulus. Sehingga hidup bersama menjadi lebih nyaman dan menggembirakan (Hidup Bersama, hal 154).
Sebagai sebuah bunga rampai kisah reflektif, buku ini tergolong komplit. Apalagi disampaikan lewat media cerita, sehingga terkesan lebih akrab. Kendati demikian, tak ada gading yang tak retak. Masih banyak kesalahan ketik yang mengganggu kenikmatan saat membaca. Selain itu, karena ditujukan untuk para remaja, pada terbitan edisi berikutnya perlu menyesuaikan gaya bahasanya dengan selera anak muda.
Akhir kata, buku ini dapat memfasilitasi sidang pembaca untuk mengembangkan benih kebajikan dalam diri. Sumber inspirasinya bukan dari teori rumit, melainkan canda-tawa dan problematika yang digeluti para siswa dalam proses pembelajaran mereka. Sepakat dengan ajakan Jessica, salah satu murid kelas 7, “Bila ingin merasa kaya, hitunglah saja semua yang engkau miliki dan tidak dapat dibeli dengan uang. Marilah kita membuat kehadiran kita menjadi hadiah terindah bagi orang-orang tercinta.” (T. Nugroho Angkasa, S.Pd, Guru Bahasa Inggris di PKBM Angon, Yogyakarta)
Judul : Lighting Candles, Renungan Bagi Remaja
Penulis : Sr. M. Levita, FSGM
Penerbit : Yayasan Dwi Bhakti
Cetakan : I/ 2011
Tebal : 236 halaman
Harga : Rp 35.000